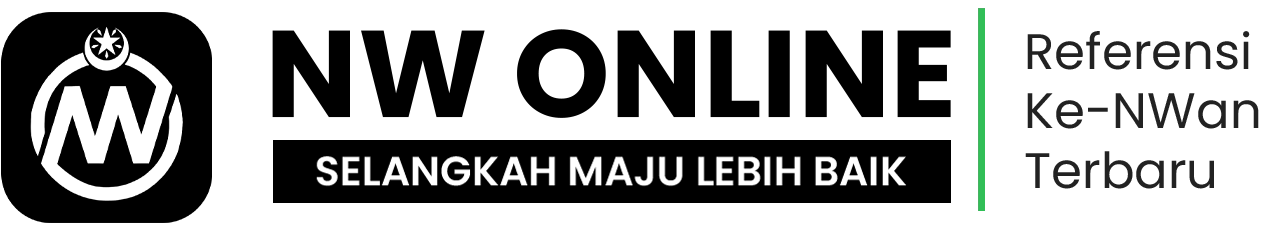Kisah dalam al-Qur’an selalu menarik untuk dikaji dan ditelaah karena tidak hanya berfungsi sebagai pembenar terhadap dakwah Nabi Muhammad, tapi juga menjelaskan bagaimana asas-asas dakwah atau cara mengajak kepada agama Allah (Mana’ Al Qaththan, 2000: 301). Diantaranya adalah kisah Nabi Ibrahim dalam surah al-An’âm ayat 75-79. Di samping itu, penafsiran terhadap al-Qur’an terus berubah dan mengalami perkembangan mengikuti zaman.
Metode atau pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur’an juga ikut mengalami perubahan, yang berdampak pada beragamanya penafsiran yang dihasilkan. Salah satu metode yang sangat seringkali digunakan di era modern ini adalah hermeneutika, sebuah metode penafsiran yang menekankan pentingnya konteks dalam memahami teks. Namun, dalam menganalisis kisah Nabi Ibrahim dalam surah al-An’âm ayat 75-79, saya akan berfokus pada hermeneutika Wilhelm Dilthey.
Pandangan Mufassir klasik dan kontemporer terhadap kisah Nabi Ibrahim surah al-An’âm/6: 76-79
Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H), diantara mufassir klasik awal, memaknai ayat-ayat ini sebagai proses perjalanan Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan. Al-Thabari kemudian memperkuat pendapatnya dengan mendatangkan satu riwayat dari Abdullah bin Abbas. Di dalam riwayat tersebut, Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah mengamati dan bahkan menganggap benda-benda langit, seperti bintang, bulan, dan matahari sebagai Tuhannya sampai akhirnya ia menyadari bahwa Tuhan yang sejati tidak mungkin tenggelam dan berubah.
Tidak hanya itu, Al Thabari juga mendatangkan potongan ayat 77 yang berbunyi “la’il lam yahdinî rabbî la’akûnanna minal-qaumidl-dlâllîn” (Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat), sebagai bantahan kepada sebagian pendapat yang menganggap bahwa seorang Nabi tidak mungkin mengalami prsoses pencarian seperti itu. (al-
Banyak mufasir klasik yang memiliki pandangan berbeda dengan Al-Thabari.
Sebut saja misalnya Ibnu Katsir (w. 774 H) di dalam kitabnya Tafsir AL-Qur’ân Al-Karîm. Dalam kitab tersebut, Ibnu Katsir justru membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat-ayat dalam surah al-An’am/6: 75-79, berbicara dalam konteks munazarah (perdebatan) Nabi Ibrahim dengan kaumnya dan menjelaskan beberapa kebatilan yang dilakukannya, bukan dalam konteks pencarian Tuhan.
Pendapatnya ini kemudian diperkuat dengan ayat setelahnya (al-An’âm/6:80) yang menunjukkan adanya perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Pada ayat setelahnya juga, tegas Ibnu Katsir, terdepat keterangan yang menjelaskna bahwa seruan tauhid Nabi Ibrahim mendapat penolakan dan bantahan dari kaumnya. Namun, Nabi Ibrahim tetep teguh dalam keyakinannya dan menolak argumentasi mereka dengan hujjah dan dalil yang kuat. ( Ibnu Katsir,1997: 3/292).
Ar-Razi (w. 604 H) dalam tafsir Mafâtih al-Ghaib yang cukup terkenal dengan penafsiran rasional, juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Ibnu Katsir, ia menjelaskan permasalahan ini dengan sangat detail dengan memberikan jawaban dari setiap asumsi “negative” terhadap Nabi Ibrahim. Dari sekian jawaban yang diberikan, paling tidak bisa disimpulakn menjadi lima. Pertama, ia menjelaskan adanya kesepakatan dikalangan ulama bahwa orang yang menaggap benda-benda langit seperti bulan, bintang, matahari dan yang lainnya sebagai tuhan dihukumi kafir dan kafir tidak boleh terjadi pada seorang Nabi.
Kedua peristiwa itu terjadi setelah Ibrahim meyakini dan mengenal Tuhannya. Ini diperkuat dengan ayat sebelumnya (QS. al-An’am: 76) yang menerangkan bahwa Ibrahim mempertanyakan ketuhanan berhala yang disembah bapaknya, Azar dan kaumnya. Selain itu, huruf fa’ pada lanjutan ayat tersebut “ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًاۗ “, menunjukkan adanya keterkaitan urutan peristiwa.
Ketiga dalam ayat-ayat tersebut Allah menghikayatkan bahwa Ibrahim mengajak ayahnya untuk mengesakan Allah dan meninggalkan sesembahannya. Keempat peristiwa yang ada dalam surah al an’am ini (ayat 76-79) muncul karena adanya perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, dan ini dikuatkan dengan ayat 83 yang mengatakan:
وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖۗ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ
“Itulah keterangan yang Kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan orang yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui.
Dalam ayat tersebut, Ar-Razi menyoroti kalimat ‘alâ qaumihî. Kalimat ini, tegasnya, sebagai indikasi kuat adanya perdebatan antara Ibrahim dengan kaumnya untuk tujuan membimbing mereka menuju keimanan dan tauhid, bukan sebagai proses pencarian agama dan pengetahuan.
Kelima dalam ayat lain, surah Ash-Shâffât/37: 84, Allah mensifatkan Nabi Ibrahim dengan qalbun salim (hati yang selamat) dan qalbun salim yang paling rendah, kata al-Razi, adalah selamat dari kekufuran. Di ayat lain, surah al-Anbiyâ’/21:51, dijelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada Ibrahim jauh sejak awal munculnya fikrah (pemikiran) itu sendiri, disamping itu Allah juga menyucikan dan menyempurnakannya, karena Allah lebih mengetahui di mana Dia akan menempatkan risalah-Nya. (al-Razi,1981: 13/50).
Diantara mufassir kontemporer yang menarik untuk dikaji pemikirannya terkait ayat-ayat ini adalah Rasyid Ridha. Dalam tafsirnya, Tafsir Al-Manar, Ridha mengkritik pendapat Al-Thabari yang menafsirkan frase hâdzâ rabbî sebagai ibadah, bagi Ridha pendapat ini tidak benar karena riwayat yang diambil berasal dari marasil Ali bin Thalhah, mantan budak Bani Abbas yang sama sekali tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas (Ridha, 2011:460). Ahmad bin Hambal juga pernah mengatakan bahwa Ali bin Thalhah ini memiliki riwayat-riwayat yang mungkar. Yang lebih menarik lagi, Ridha mengherankan sikap Al-Thabari yang memilih pendapat ini, padahal ia sendiri telah menjelaskan pendapat yang berlawanan dengannya dengan cara yang baik.
Hermeneutika Historis Wilhelm Dilthey dalam Menafsirkan Surah al-An’âm Ayat 75–79
Wilhelm Dilthey, seorang filsuf Jerman yang lahir pada 19 November 18833, pemikirannya memberikan kontribusi besar dalam pengembangan metode penafsiran. Ia mengembangkan pendekatan hermeneutika yang menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks sejarah dan pengalaman hidup pengarangnya.
Teori hermeneutik yang tawarkan Dilthey melalui tiga tahapan. Pertama, Erlebnis merupakan pemahaman yang didasarkan pada pengalaman nyata yang dilalui penulis teks (pengalaman yang hidup). Kedua, Ausdruck adalah bentuk ekspresi atau penyampaian pengalaman dalam teks (ungkapan). Ketiga, Verstehen adalah proses mendalam untuk memahami makna yang ada di balik ekspresi atau ungkapan teks tersebut (pemahaman). (Hardiman, 2015: 82). Menurut Dilthey, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu teks, kita tidak bisa mengabaikan konteks sejarah dan sosial di mana teks tersebut diciptakan. Oleh karena itu, dalam memahami berbagai jenis teks—baik itu teks sejarah, sastra, maupun teks keagamaan seperti Al-Qur’an—penting untuk memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melatarbelakangi masa penurunannya. (Putri, 2022)
Dalam konteks tafsir Surah al-An’âm ayat 75–79, pendekatan ini membantu kita memahami bahwa kisah Nabi Ibrahim bukan sekadar proses pencarian Tuhan secara pribadi, melainkan merupakan strategi dakwah yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat pada masa itu. Nabi Ibrahim menggunakan metode dialogis dan argumentatif untuk mengajak kaumnya berpikir kritis terhadap keyakinan mereka, dengan menyampaikan pernyataan seperti “hâdzâ rabbî” (ini Tuhanku) sebagai bagian dari strategi dakwahnya.
Pertama: Erlebnis (Pengalaman Hidup)
Dalam tahap ini, kita memahami bahwa pengalaman batin Nabi Ibrahim bukan hanya pencarian personal atas Tuhan yang sejati, tetapi juga pergumulan eksistensial dalam menghadapi masyarakat musyrik yang menyembah benda-benda langit. Nabi Ibrahim mengalami realitas sosial yang penuh penyimpangan akidah, dan ia tidak sekadar menolak secara pasif, melainkan mengalami keresahan yang mendorongnya untuk menyusun strategi dakwah yang sesuai dengan daya nalar masyarakat. Jadi, Erlebnis tidak hanya bermakna spiritual individual, tetapi juga kesadaran sosial dan tanggung jawab profetik terhadap penyimpangan kolektif kaumnya.
Kedua: Ausdruck (Ekspresi Pengalaman)
Ausdruck dalam konteks ini berarti cara Nabi Ibrahim mengartikulasikan pengalamannya dalam bentuk komunikasi yang persuasif dan strategis.
Pernyataan seperti:
“Hâdzâ rabbî” (Ini Tuhanku)
…tidak bisa dimaknai secara literal sebagai keyakinan sementara, tetapi merupakan bagian dari retorika dakwah Ibrahim yang bersifat ironi atau sindiran halus, untuk mengajak kaumnya berpikir. Ini adalah bentuk dari ekspresi pedagogis yang menyesuaikan diri dengan nalar masyarakat penyembah benda langit, yang terbiasa menyamakan cahaya dan keagungan dengan ketuhanan. Maka, ekspresi ini adalah metode dakwah berbasis dialog kritis, bukan hanya ekspresi spiritual personal.
Ketiga: Verstehen (Pemahaman Historis)
Tahap Verstehen menuntut kita memahami struktur sosial, kepercayaan budaya, dan kecenderungan religius masyarakat masa itu. Dalam konteks masyarakat Ibrahim yang mengagungkan benda-benda langit, ekspresi dakwah seperti “ini Tuhanku” adalah strategi untuk mengajak berpikir kritis lewat pendekatan logis dan retoris yang akrab di telinga mereka.
Pemahaman historis ini menunjukkan bahwa kisah Ibrahim bukan sekadar narasi spiritual, tetapi juga potret perjuangan intelektual dan sosial. Ia mencontohkan bahwa dakwah harus: Memahami cara berpikir audiens, Menggunakan pendekatan induktif (dari fenomena menuju kesimpulan teologis), Memanfaatkan perenungan kosmik sebagai media dakwah rasional.
Dengan begitu, Verstehen menjadikan kita tidak membaca kisah Ibrahim secara ahistoris atau semata-mata dari sisi spiritual, tapi sebagai teladan komunikasi profetik yang sangat relevan untuk misi keagamaan kontekstual hari ini.
Dengan demikian, pendekatan hermeneutika historis Dilthey memberikan perspektif yang mendalam di dalam memahami kisah Nabi Ibrahim, tidak hanya sebagai narasi sejarah, tetapi juga sebagai ekspresi dari pengalaman hidup dan konteks sosial-historis pada masa itu. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami lebih baik bagaimana ajaran Nabi Ibrahim diterapkan dalam kehidupan sosial yang berubah-ubah dan bagaimana ia berinteraksi dengan kaumnya untuk membimbing mereka menuju kebenaran.
Referensi Bacaan;
Ibnu Jarir Al-Thabari, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān, Dâr al Hadits
Mana’ Al Qaththan, Mabāhits fî ‘Ulûm al-Qur’ân, Maktabah Wahbah
Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, Dâr al-Fikri
Ibnu KAtsir, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim, Dār Ṭayyibah
Muḥammad Rashīd Riḍā, Tafsīr al-Manār
Hardiman, F. Budi. Seni Memahami: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida. Depok: Kanisius, 2015.
Putri, Rachmawati. “Arti Penting Sejarah dalam Tinjauan Dilthey.” Dalam https://Ibihtafsir.Id/2022/02/25/Arti-Penting-Sejarah-Dalam-Tinjauan Dilthey/ Dikases Pada 10 November 2024.
Biodata Penulis:
Nama : Muhammad Ramli Saldiman
Email : rsaldiman@gmail.com
Alumni MDQH NW Anjani Angkatan 48
Punya karya tulis? Saatnya dipublikasikan! Gesit Kirim tulisan Anda dan biarkan NW Online membagikannya ke seluruh Nusantara. Kontak WA: 08567892305.